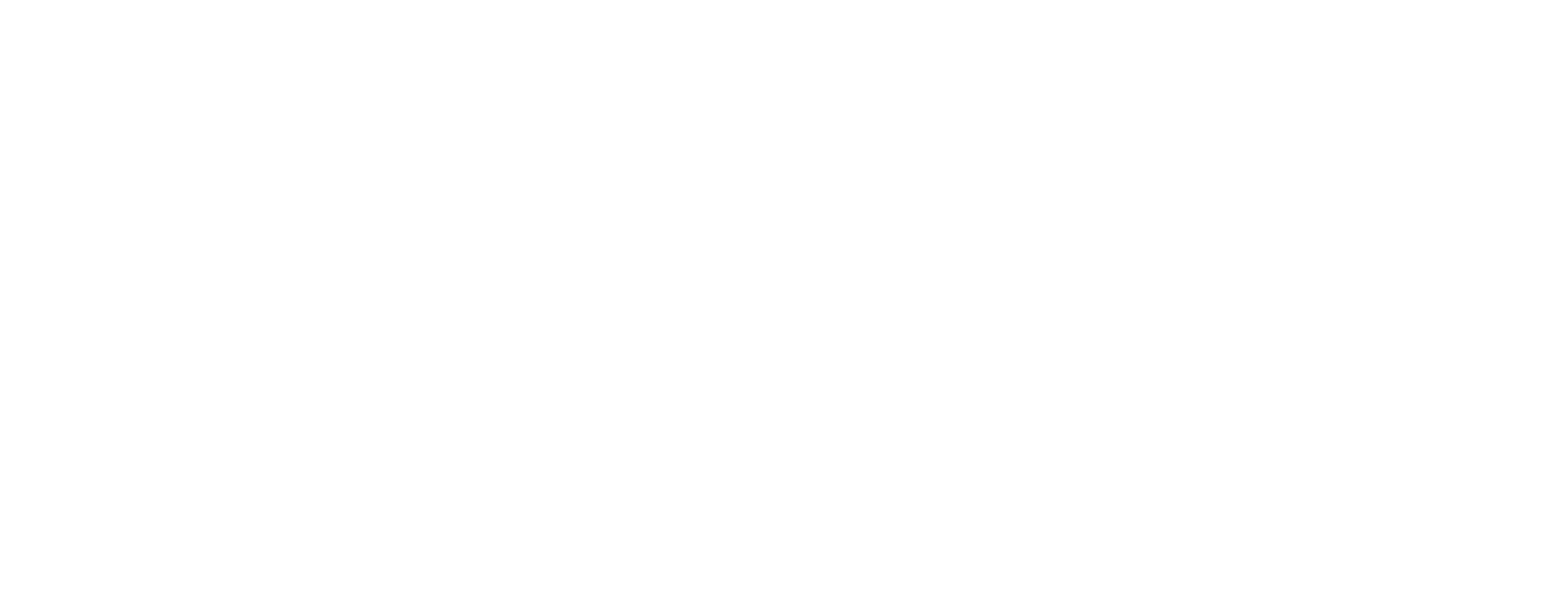INTEGRASI LAYANAN ANAK PADA PERPUSTAKAAN DALAM PEMBANGUNAN KOTA LAYAK ANAK

Konsep Kota Layak Anak bertitik tolak dari Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan hak setiap anak untuk tumbuh sehat, mendapat perlindungan, dan berkembang secara optimal. Kota Layak Anak (Child-Friendly City) adalah kota yang secara sistematis berkomitmen meningkatkan kualitas hidup anak dengan mewujudkan hak-hak anak dalam kebijakan, program, dan keputusan publik.
Dalam praktiknya, kota layak anak ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan lingkungan yang ramah. Secara ringkas, beberapa ciri utama kota layak anak meliputi:
- Perlindungan dan Kesehatan: Anak terlindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan kekurangan gizi, serta tumbuh sehat dan diasuh dengan baik.
- Layanan Sosial dan Pendidikan Berkualitas: Anak mendapat akses layanan sosial dan pendidikan yang berkualitas secara inklusif.
- Partisipasi dan Hak Suara: Anak dapat menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi mereka.
- Lingkungan Aman dan Nyaman: Tersedia lingkungan yang aman, bersih, dengan ruang hijau dan area bermain, sehingga anak dapat bersosialisasi dan berekreasi.
- Kesetaraan Peluang: Setiap anak memiliki kesempatan setara, tanpa diskriminasi atas latar belakang apapun.
Ciri-ciri di atas menunjukkan pentingnya layanan publik yang ramah anak, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan budaya, yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus anak. Pandangan ini didukung oleh Child Friendly Cities Initiative UNICEF yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus meletakkan hak-hak anak (seperti diatur dalam CRC) di pusat kebijakan kota. Oleh karena itu, implementasi kota layak anak mensyaratkan kolaborasi lintas sektor (pemerintah, masyarakat sipil, dan anak-anak sendiri) dalam merancang layanan publik.
Perpustakaan umum merupakan institusi strategis yang berperan penting dalam memenuhi hak-hak anak di kota layak anak. Perpustakaan menyediakan akses informasi, edukasi, dan budaya yang mendukung hak-hak anak. Menurut KHA Pasal 28, setiap anak berhak atas pendidikan, dan Pasal 17 menyatakan anak berhak memperoleh informasi dari buku dan media lainnya . Selain itu, Pasal 31 menegaskan hak anak atas istirahat, bermain, dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya serta kreatif. Perpustakaan anak bertindak sebagai wujud pelayanan publik yang merealisasikan hak-hak tersebut. Sebagai contoh, Chawla dan van Vliet (2017) mencatat bahwa “hak anak atas kota” meliputi akses ke sumber daya perkotaan seperti sekolah, layanan kesehatan, ruang bermain, perpustakaan, dan fasilitas publik lainnya. Dengan kata lain, akses anak ke perpustakaan merupakan bagian inheren dari hak mereka untuk belajar dan berkembang di lingkungan kota.
UNESCO juga menekankan pentingnya perpustakaan dalam konteks ini. Deklarasi IFLA-UNESCO Public Library Manifesto menyebut perpustakaan publik sebagai institusi vital untuk pendidikan, budaya, inklusi, dan informasi, serta agen penting bagi perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, perpustakaan bukan hanya tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat pembelajaran seumur hidup dan kesetaraan informasi. Kontribusi perpustakaan dalam pendidikan dan literasi anak semakin diperkuat oleh prakarsa prakarsa lokal, seperti Taman Bacaan Pelangi di Indonesia. Melalui program penyediaan perpustakaan anak di daerah terpencil, Taman Bacaan Pelangi mendorong minat baca anak-anak dengan menyediakan buku-buku berkualitas. Mereka menyatakan bahwa akses buku amat penting bagi pendidikan anak dan mampu memperluas wawasan serta membuka peluang baru bagi mereka. Hal ini memperlihatkan bagaimana perpustakaan (baik formal maupun komunitas) dapat menginspirasi mimpi anak dan memutus lingkaran kemiskinan melalui literasi.
Dengan demikian, perpustakaan memainkan peran ganda dalam kota layak anak: menyediakan infrastruktur belajar dan budaya bagi anak-anak, serta berfungsi sebagai ruang inklusif tempat anak dapat tumbuh dan berkreasi. Perpustakaan membantu merealisasikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan informasi serta berpartisipasi dalam kehidupan budaya kota.
Integrasi layanan anak di perpustakaan berarti memasukkan peran perpustakaan anak ke dalam rencana pembangunan kota layak anak. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan program terpadu antar dinas terkait (pendidikan, perpustakaan, kesehatan, sosial, dan perencanaan). Misalnya, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan perpustakaan ramah anak sebagai bagian dari indikator kota layak anak. Selain itu, perpustakaan harus dilibatkan dalam jaringan pemantauan keberhasilan kota layak anak, bersandingan dengan sekolah, pusat kesehatan, taman bermain, dan fasilitas publik lainnya.
Dalam strategi ini, pendekatan multi-pemangku kepentingan sangat dianjurkan. Child Friendly Cities Initiative (CFCI) UNICEF menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, media, dan anak-anak sendiri. Dengan melibatkan komunitas dan pakar pendidikan, perpustakaan anak dapat lebih mudah merancang program yang sesuai kebutuhan lokal. Misalnya, perpustakaan bekerja sama dengan sekolah untuk menghadirkan penulis anak ke sekolah atau menyelenggarakan lomba membaca. Kolaborasi dengan dinas sosial dan kesehatan dapat menghadirkan penyuluhan gizi atau pemeriksaan kesehatan anak di area perpustakaan. Kemitraan dengan pihak swasta dan LSM literasi (seperti Taman Bacaan Pelangi) bisa menambah koleksi buku dan relawan pendongeng.
Secara teknis, integrasi layanan perpustakaan anak ke dalam pembangunan kota layak anak dapat mencakup langkah-langkah praktis seperti: memasukkan perpustakaan anak dalam rencana tata ruang kota (misalnya, desa/kelurahan menetapkan “Taman Baca” dalam masterplan), menyediakan transportasi ramah anak ke perpustakaan (angkutan gratis bagi pelajar), serta mengembangkan aplikasi digital layanan perpustakaan yang mudah diakses anak. Dalam perencanaan program, perpustakaan anak sebaiknya dipandang sebagai pusat komunitas belajar yang mendukung berbagai aspek hak anak, mulai dari literasi awal, pendidikan STEM, hingga perkembangan sosial-budaya anak. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa suara dan kebutuhan anak harus diakui dalam kebijakan publik kota layak anak.
Perpustakaan ramah anak idealnya menyediakan berbagai layanan spesifik yang merangsang minat belajar dan kreativitas anak. Beberapa contoh layanan dan fasilitas yang dapat diintegrasikan antara lain:
•Area Baca Khusus Anak: Ruang dengan desain dan furnitur yang disesuaikan untuk anak-anak, lengkap dengan koleksi buku cerita dan referensi bergambar yang menarik. Katalog buku harus mencakup literatur lokal, dongeng tradisional, dan buku pelajaran ringan. Seperti yang digagas Taman Bacaan Pelangi, akses mudah ke buku-buku berkualitas akan memperluas wawasan anak-anak dan memupuk mimpi mereka.
•Program Literasi Dini dan Dongeng: Perpustakaan secara rutin menyelenggarakan kegiatan membaca bersama (storytelling), teater boneka, workshop mendongeng, atau kelas menulis kreatif untuk anak usia dini. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi awal tetapi juga mengasah kemampuan berbahasa dan imajinasi anak.
•Layanan Digital Edukatif: Menyediakan komputer atau tablet dengan konten edukatif dan program belajar interaktif (misalnya e-buku interaktif, permainan edukasi, coding anak). Literasi digital penting untuk anak di era modern, sehingga pelatihan dasar penggunaan komputer dan internet sehat sebaiknya diberikan.
•Program Sains dan Kreativitas: Menawarkan lokakarya atau demo sains sederhana, eksperimen, serta kegiatan seni dan musik yang melibatkan anak-anak. Hal ini dapat menumbuhkan minat terhadap sains dan budaya sekaligus menyalurkan bakat anak di luar kurikulum formal.
•Layanan Inklusif: Fasilitas perpustakaan harus ramah bagi semua anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Misalnya, koleksi buku Braille atau audio, ruang permainan untuk anak penyandang disabilitas, dan penyesuaian bangunan (ram untuk kursi roda, toilet anak). Program khusus juga dapat mencakup buku dalam bahasa ibu minoritas atau fasilitas penerjemah bahasa isyarat.
•Perpustakaan Keliling atau Unit Kelompok Baca: Untuk menjangkau anak di daerah terpencil atau terpinggirkan, pemerintahan kota dapat bekerja sama dengan perpustakaan keliling atau mendukung rumah baca komunitas.
•Kemitraan Sekolah dan Komunitas: Perpustakaan mengadakan kegiatan bersama dengan sekolah (misalnya lomba perpustakaan antar sekolah, program les privat eksrakurikuler) dan komunitas anak muda (seperti klub coding atau klub buku anak). Kegiatan kolaboratif ini membantu memperkuat jejaring pendukung kota layak anak.
Dengan layanan-layanan ideal di atas, perpustakaan tidak hanya menjadi gudang buku, tetapi juga ruang bermain dan belajar yang aman serta menyenangkan bagi anak. Hal ini sejalan dengan ruh kota layak anak yang mengutamakan tempat agar anak “dapat bertemu teman, bermain, dan bersenang-senang”.
Integrasi layanan anak di perpustakaan dalam pembangunan kota layak anak tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa kendala umum yang sering dihadapi antara lain: keterbatasan anggaran daerah untuk perpustakaan, kurangnya pustakawan terlatih khusus anak, serta sarana prasarana perpustakaan yang belum memadai. Tidak semua pemerintah daerah secara otomatis memasukkan layanan anak ke perpustakaan dalam rencana kerja mereka. Selain itu, adaptasi teknologi dan preferensi baru anak (misalnya kecenderungan bermain gadget) juga mengubah cara perpustakaan merencanakan layanan. Tantangan lain adalah sinkronisasi antar instansi (pendidikan, perpustakaan, sosial) yang masih terkotak-kotak sehingga upaya kolaboratif belum optimal. Misalnya, perpustakaan bisa saja tidak memperoleh akses data anak miskin untuk program literasi karena belum terintegrasi dalam sistem data sosial kota.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan terpadu. Pertama, dukungan kebijakan dan anggaran harus ditingkatkan. UNESCO (2023) menegaskan bahwa negara anggota perlu memperkuat peran perpustakaan melalui kebijakan yang jelas dan dukungan pendanaan. Pemerintah kota dapat menetapkan standar minimum sarana perpustakaan ramah anak dalam kebijakan KLA, serta memprioritaskan anggaran untuk melengkapi koleksi buku anak dan fasilitas pendukung. Kedua, peningkatan kapasitas SDM sangat penting. Pelatihan pustakawan anak secara rutin (misalnya manajemen acara anak, konseling literasi) dapat meningkatkan kualitas layanan. Pustakawan perlu dipandang sebagai pendidik dan fasilitator anak, bukan sekadar penjaga buku.
Ketiga, pembangunan kemitraan lintas sektor. Perpustakaan harus aktif berkolaborasi dengan NGO, perguruan tinggi (untuk riset literasi), dan organisasi relawan. Kontribusi masyarakat pun krusial; pengalaman Taman Bacaan Pelangi menunjukkan bahwa “semakin banyak kontribusi dari berbagai pihak, semakin banyak anak di daerah terpencil yang memperoleh akses buku”. Program donasi buku dan sukarelawan guru baca di perpustakaan dapat diperbanyak. Keempat, pemanfaatan teknologi dapat dijadikan solusi. Platform perpustakaan digital (e-library) dan aplikasi mobile bisa memperluas jangkauan anak untuk mengakses buku meski jauh dari gedung perpustakaan.
Akhirnya, monitoring dan evaluasi integrasi layanan anak harus dilakukan secara terukur. Alat pemantauan kota layak anak (indeks KLA) harus memasukkan indikator layanan perpustakaan anak, misalnya jumlah kegiatan literasi per tahun atau persentase sekolah yang rutin mengunjungi perpustakaan. Pengakuan publik (akreditasi atau penghargaan perpustakaan layak anak) juga dapat menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat layanan ini.
Pengintegrasian layanan anak di perpustakaan merupakan aspek krusial dalam mewujudkan kota layak anak. Perpustakaan anak menyediakan sarana pendidikan, informasi, dan rekreasi yang mendukung pemenuhan hak anak, seperti yang ditekankan dalam CRC. Dalam kerangka kota layak anak, perpustakaan adalah bagian penting dari infrastruktur sosial yang harus diperlakukan secara strategis. Dengan mengoptimalkan layanan anak di perpustakaan — mulai dari area baca menarik hingga program kolaboratif literasi — kota dapat memastikan bahwa hak-hak anak (pendidikan, informasi, partisipasi, dan lingkungan bermain) terakomodasi secara baik. Tantangan yang ada dapat diatasi melalui dukungan kebijakan, pendanaan, pelatihan, dan kemitraan luas. Pada gilirannya, integrasi layanan perpustakaan anak ini akan memperkuat indikator keberhasilan pembangunan kota layak anak. Dengan kata lain, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pilar penting dalam mewujudkan masyarakat kota yang benar-benar ramah dan berorientasi pada masa depan anak-anak.
Daftar Pustaka
Child Friendly Cities Initiative. (n.d.). What is a child-friendly city? Diakses dari https://www.childfriendlycities.org/what-is-a-child-friendly-city
Chawla, L., & van Vliet, W. (2017). Children’s rights to child-friendly cities. [PDF]. University of Colorado, Boulder. (Diakses dari https://www.colorado.edu/cedar/sites/default/files/attached-files/chawla_van_vliet_childrens_right_to_child_friendly_cities_finaljuly30-1.pdf )
UNICEF. (n.d.). The Convention on the Rights of the Child: The children’s version. Diakses dari https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version
UNESCO. (2023, 26 April). Updated Public Library Manifesto 2022 generates global and national impact on public libraries. UNESCO News. Diakses dari https://www.unesco.org/en/articles/updated-public-library-manifesto-2022-generates-global-and-national-impact-public-libraries
UNESCO Inclusive Policy Lab – Taman Bacaan Pelangi. (n.d.). Yayasan Pelangi Impian Bangsa: Taman Bacaan Pelangi. Diakses dari https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/users/taman-bacaan-pelangi
WHO, et al. (2019). Building child friendly cities: A framework for action. Save the Children (merujuk pada prinsip pembangunan kota layak anak secara global).

Ketua TPPS Lamongan Ajak Tertib Data Untuk Penanganan Tepat Sasaran

Dua Inovasi Pemkab Lamongan Masuk Nominasi IGA 2025

Kabupaten Lamongan Menempati Peringkat Pertama Produksi Padi se-Jawa Timur

Kabupaten Lamongan Mendapat Apresiasi Atas Progres KDMP

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Semakin Mudah

Pemerintah Kabupaten Lamongan Dukung Pemberdayaan Difabel

Kemantapan Jalan Lamongan Per Oktober 2025 Mencapai 59,97 persen

Hari Sumpah Pemuda ke-97, Pemkab Lamongan Apresiasi Pemuda Solokuro Yang Dukung Ketahanan Pangan

1.700 Hektar Sawah di Kembangbahu Siap Panen MT III

Peringatan Hari Santri Di Lamongan Semarak